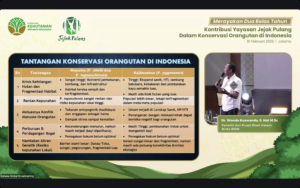Jakarta, SenayanTalks — Hutan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyimpan potensi ekonomi luar biasa. Laporan terbaru dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menyebut bahwa total valuasi ekonomi hutan Morowali mencapai Rp2,81 triliun per tahun—angka ini 44,61% lebih tinggi dari realisasi pendapatan daerah tahun 2023 yang hanya sebesar Rp1,94 triliun.
Namun, potensi besar ini terancam. Sebanyak Rp1,07 triliun dari nilai tersebut berada di dalam konsesi tambang nikel. Jika ekspansi tambang terus dilakukan, kerugian ekonomi akibat hilangnya jasa lingkungan hutan bisa meningkat hingga Rp568 miliar per tahun.
Laporan AEER menggunakan pendekatan Total Economic Value (TEV) sesuai Permen LH No. 15 Tahun 2012. Penelitian ini menilai nilai langsung dan tidak langsung dari hutan, termasuk jasa lingkungan, nilai keberadaan, dan nilai warisan. Penilaian dilakukan dengan teknik overlay peta spasial dan pendekatan pasar serta biaya pengganti.
“Morowali adalah kawasan kaya nikel dan biodiversitas. Ketidakseimbangan eksploitasi tambang tanpa perlindungan hutan justru merugikan jangka panjang,” ujar Risky Saputra, peneliti AEER.
Sejak 2019 hingga 2023, tambang nikel telah menyebabkan deforestasi seluas 37.660 hektare, menghasilkan emisi hingga 28,7 juta ton CO₂e. Sebanyak 6.110 hektare deforestasi tersebut terjadi di wilayah tambang Morowali.
Hutan Morowali saat ini mampu menyerap 1,1 juta ton karbon per tahun, menjadikannya aset penting untuk target FoLU Net-Sink 2030 Indonesia, yaitu netral karbon sektor kehutanan pada 2030. Namun, ancaman tambang dapat menggerus kontribusi tersebut.
Sebanyak 157.935 hektare (35% wilayah Morowali) kini sudah dikonversi menjadi konsesi tambang nikel yang mencakup 70 perusahaan. Dari jumlah itu, 97.790 hektare merupakan hutan primer yang seharusnya dilindungi.

AEER merekomendasikan moratorium izin baru di hutan primer dan kawasan bernilai keanekaragaman tinggi, integrasi potensi keuangan dari perlindungan ekosistem ke RPJMD, RPJMN, dan SNDC serta optimalisasi pendanaan restorasi lingkungan berbasis hasil (result-based finance).
Guru Besar Ekonomi SDA dan Lingkungan IPB, Akhmad Fauzi, menekankan pentingnya melihat hutan sebagai natural capital, bukan sekadar sumber daya produksi. “APBD Morowali kalah jauh dari nilai sumber daya alamnya,” katanya.
Ia juga mendorong pembentukan resource fund dari hasil eksploitasi SDA yang dikembalikan ke daerah dalam bentuk penguatan ekonomi lokal seperti wisata alam dan jasa lingkungan.
Morowali adalah rumah bagi spesies endemik seperti burung Maleo (Macrocephalon maleo), Rangkong Sulawesi (Rhyticeros cassidix), dan Monyet Butung (Macaca ochreata). Tekanan terhadap habitat mereka terus meningkat akibat ekspansi tambang.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Sulawesi Tenggara, Subhan Basir, menyatakan laporan AEER akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD 2025–2029.
Laporan AEER “Ekonomi Hijau di Ujung Tanduk” menegaskan bahwa hutan Morowali memiliki nilai strategis baik secara ekonomi, ekologis, maupun diplomasi iklim internasional. Jika tidak segera diintervensi secara kebijakan, deforestasi akibat tambang akan menjadi beban besar bagi Indonesia dalam mencapai target iklim global.
Baca juga :
Warga Golewa Selatan Tolak Eksploitasi Air Tiwu Bala untuk Proyek Geotermal PLN
Pencemaran Plastik Ancam Mangrove di Surabaya, ECOTON Desak Tanggung Jawab Produsen